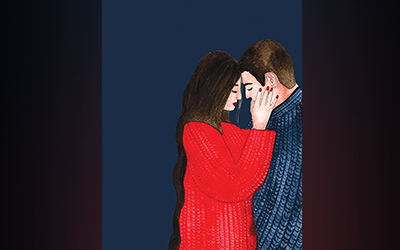Aku memandang nanar ke arah perkampungan suku laut di tepi Pulau Binta, Riau, itu dari arah sampan yang aku naiki. Terlihat sepasang suami-istri tua dan seorang pemuda yang menggendong anaknya sedang melambai ke arahku. Itu Abah, Ampu, Alun, abangku, dan Menan, anak Alun. Seketika darahku berdesir. Ada kerinduan yang mengalir di sekujur tubuhku, melemaskan persendianku, memanaskan mataku.
Sampanku mendekati rumah besar itu. Ampu segera memelukku ketika aku berhasil naik ke atas rumah. Lirih beliau menyanyikan sebuah lagu di sela isak tangisnya, membuatku teringat akan kejadian-kejadian beberapa tahun silam.“Soleram, sol-soleram, soleram anak yang manis, anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya.”
Ampu mencium keningku hangat seraya membelai rambut panjangku. Malam ini, seperti biasa, Ampu menyanyikan dodoi* sebelum aku tidur. Lagu daerah kesukaanku dari kecil, Soleram. Namun, malam ini langit sangatlah cerah. Bintang-bintang benar-benar bertaburan, seperti garam yang tumpah dari genggaman. Membuatku ingin terjaga lebih lama.
“Ampu,” aku menarik baju Ampu yang hendak keluar dari bilik sampan. “Ampu, aku mau melihat bintang,” rengekku lirih seraya bangkit dari tidur. Ampu tersenyum, lalu menggandengku keluar bilik. Angin malam lautan yang liar dan kencang menyambutku seketika. Membuatku merapatkan kain yang semula aku pakai sebagai selimut.
“Sini, Nak, tidur di pangkuan Ampu. Biar Ampu nyanyikan kau dodoi sampai kau terlelap. Di sini, kau bisa melihat lintang di langit,” ucap Ampu seraya duduk selonjor dan bersandar di depan bilik sampan.
Aku segera tidur dengan kepala berpangku pada paha Ampu. Ampu sudah mulai menyanyikan Soleram ketika aku tersadar akan sesuatu. “Ampu, lihat itu! Sebuah bintang berwarna biru. Besar sekali Ampu. Paling besar daripada bintang-bintang lain. Cantik sekali!” seruku seraya menunjuk ke arah bintang yang aku lihat tadi.
Ampu mendongak, melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari telunjuk mungilku.
“Azurea,” bisik ampu.
“Ya, Ampu. Ada apa?” ucapku, seraya memandang kedua mata Ampu. Mata bulat besar dengan bola mata hitam-kecokelatan yang sama persis dengan warna bola mataku.
“Azurea, apa Abah pernah bercerita pada kau apa arti namamu, Nak?” tanya Ampu dan aku hanya menggeleng kecil.
Ampu melanjutkan, “Azurea itu artinya biru.”
“Seperti warna bintang itu ya, Ampu?” potongku.
Ampu tersenyum. “Ya, seperti bintang itu. Juga seperti warna lautan. Tempat warga suku laut tinggal. Biru.”
“Kalau namaku artinya apa Ampu?” tiba-tiba Alun, abangku, sudah berada di pintu bilik, sepertinya dia terbangun karena suaraku dan Ampu.
“Ombak. Gelombang laut,” jawab Ampu, seraya memeluk Alun yang duduk di sampingnya. Ampu melanjutkan ceritanya, “Anak-anakku, Ampu hanya ingin berpesan pada kalian untuk tetap menjaga resam* suku laut. Abah kalian itu sangat mencintai lautan dan suku kita. Karena itulah, kalian diberi nama Azurea dan Alun.”
Kami adalah lanun*, suku laut yang hidup nomaden di atas sampan-sampan kayu. Nelayan andal yang seakan tak pernah takut pada besarnya ombak. Suku yang pernah menjadi kepercayaan Kesultanan Malaka untuk menjaga mereka. Suku yang kemudian tersingkirkan karena kedatangan bangsa Bugis dengan segala macam alat melaut mereka yang lebih modern.
HARI INI aku dan Alun diminta Abah ke kota untuk membeli obat karena Ampu tiba-tiba sakit dan tidak mau ditinggal Abah. Ini pertama kalinya aku ke kota! Aku sungguh tak bisa melepaskan pandanganku dari hiruk-pikuknya. Dari keragaman dan warna-warni kota, dari apa yang tak pernah kulihat di tengah laut.
Rasanya hampir putus kakiku ketika akhirnya Alun berhenti di depan sebuah toko dengan pelang besar bertuliskan “Azam”. Toko itu begitu ramai. Antrean pembeli toko tua bercat cokelat muda itu mengular.
“Azurea, tunggulah kau di bawah pohon kelapa itu. Biar Abang yang mengantre,” perintah Alun, seraya menunjuk sebuah pohon kelapa di seberang Toko Azam. “Ingat, jangan ke mana-mana sebelum aku kembali,” ancam Alun dengan wajah serius dan jari telunjuk mengacung-acung di depan hidungku. Aku hanya mengangguk kecil dan segera berlari ke arah pohon kelapa yang Alun tunjuk.
Bruk... Tanpa sengaja aku menabrak sesosok tubuh yang tak kukenal. Aku terhuyung ke belakang. Tubuhku mendarat kasar ke atas tanah. Kulihat sosok yang aku tabrak tadi pun jatuh tepat di depanku. Dia meringis kesakitan, lalu segera merapikan foto-foto yang jatuh berserakan dari tas pinggangnya. Aku mencoba membantu anak itu mengumpulkan foto-fotonya. Foto-foto yang membuat darahku bergejolak dan tubuhku seakan tersengat aliran listrik ikan sidat ketika melihatnya.
“Kau tidak apa-apa?” tanya anak yang aku tabrak tadi seraya mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku mundur beberapa langkah. Anak itu terus menatapku. Aku segera berlari ke arah pohon yang tadi Alun tunjuk. Aku takut Alun akan marah padaku jika tahu aku berbincang dengan orang asing, karena sudah jadi adat warga suku laut untuk agak menutup diri dari dunia luar. Berupaya menghindari masuknya pengaruh buruk dari budaya lain.
Anak laki-laki yang aku tabrak tadi berjalan ke arahku. “Kau membawa foto-fotoku!” ucap anak itu lirih saat berdiri tepat di depanku.
“Maaf.” Aku menundukkan kepala dan menyodorkan foto-foto tadi.
“Namaku Hygi,” ucap anak tadi dan duduk di sampingku. “Siapa namamu?”
“Azurea.”
“Namamu bagus. Tidak seperti nama orang Bintan.” Hening sesaat.
“Aku bukan orang Bintan. Aku orang Riau. Aku di sini untuk menemani ayahku. Beliau fotografer,” papar anak itu dengan logat yang sangat aneh dan menurutku lucu.
“Kertas-kertas apa yang tadi kau bawa Hygi?” tanyaku ragu.
“Oh ini. Ini adalah foto-foto yang aku ambil saat aku menemani ayahku ke beberapa negara.”
Aku mengangguk mantap dan sedetik kemudian sudah tenggelam dalam cerita Hygi tentang foto-foto yang dia ambil. Ada foto gunung berwarna biru seperti laut yang kata Hygi namanya adalah Gunung Fuji. Ada foto bangunan yang condong ke kanan yang kata Hygi namanya menara miring Pisa. Bahkan ada pula foto sebuah bangunan yang sangat besar namun sudah sedikit hancur bernama Coloseum.
Tapi tetap, yang paling memukauku adalah foto taman bunga yang berwarna-warni. Seperti warna bintang-bintang di langit. Seperti warna terumbu-terumbu karang di laut. Seperti warna kue-kue yang tadi aku lihat dijajakan tanpa ditutup apa pun di pasar. Aku merasakan euforia berlebihan ketika melihat foto itu. Seperti pukau*, foto itu mampu membuat mataku seakan tak mau mengalihkan pandanganku pada apa pun. Dan Hygi memberikan foto itu kepadaku.
Aku mulai berpikir, jika ada tempat seindah itu, kenapa aku hanya menghabiskan hari-hariku di laut? Jika ada begitu banyak warna, kenapa hanya biru yang selalu aku lihat? Dan jika dunia begitu luas, kenapa tak kudatangi saja tiap sudutnya? Seulas senyum tersungging di bibirku. Seperti nama toko tadi, Azam. Dalam bahasa Melayu, azam berarti cita-cita, mimpi. Kini aku telah menemukan azam-ku. Azam yang akan membawaku melihat dunia yang luas ini. Melihat berjuta warna.
“AZUREA!” teriak Alun tepat di telingku. Membuatku terlonjak kaget dan hampir menjatuhkan foto pemberian Hygi ke laut. “Melamun sajo kau ini. Aku hendak ke kota menemani Abah menjual tenggiri. Kau bantulah Ampu memasak sotong!” perintah Alun seraya naik ke atas sampan kecil yang biasa kami gunakan untuk berlabuh ke Pulau Bintan.
“Kau hendak ke kota, Bang?” mataku membulat, aku sangat ingin bertemu Hygi lagi, aku ingin mendengar ceritanya tentang warna-warni dunia, tentang bunga tulip yang cantik. “Aku ikutlah, Bang. Aku sangat ingin ke kota lagi.”
“Tidak Azurea! Kau temani Ampu sajo di rumah. Masak yang enak. Nanti aku dan Abah akan pulang bawa banyak jajanan pasar kesukaan kau,” ucap Alun, seraya mendayung sampannya menjauhi sampan tempatku berdiri.
“Ampu, Azurea hendak bercerita pada Ampu. Tapi, Ampu jangan marah, ya, setelah Azurea bercerita?” ucapku lirih, seraya meletakkan sotong-sotong yang telah aku cuci ke dalam tembikar.
“Ceritalah. Biar Ampu tahu apa yang membuat roman* wajahmu sesedih itu, anakku,” ucap Ampu, seraya membelai pipiku lembut.
“Sebenarnya Azurea ingin…,” aku kembali diam, tanganku sampai meremas-remas ujung bajuku karena gugup. Aku mendekati Ampu dan berbisik di telinga beliau, “Aku ingin bersekolah. Aku ingin menjadi anak pandai. Aku ingin melihat dunia.”
Aku tahu aku salah, tapi aku tak tahu letak kesalahanku. Aku hanya ingin bersekolah. Apa itu salah? Apa itu dosa? Bukankah banyak hal yang perlu kita pelajari lebih dari sekadar berlayar dan berlayar. Bukankah ada berjuta ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan suku laut?
Karena pertanyaan-pertanyaan itulah aku berada di sini. Di depan sampan milik Tsaman*. Sosok bijaksana, pemimpin warga suku laut di Pulau Bintan.
“Kemarilah, Nak. Utarakan apa yang ingin kau tanyakan! Tsaman dengar, kau sangat ingin bersekolah, apa benar?” tanya Tsaman, seraya menyesap minumannya.
Aku hanya mengangguk.
“Kau tahu suku laut berbeda?”
Aku kembali mengangguk menjawab pertanyaan Tsaman.
Aku memperlihatkan foto pemberian Hygi kepada Tsaman. Tsaman sedetik kemudian terpukau, hanya sedetik, lalu kembali menyesap minumannya lagi sebelum menarik napas panjang.
“Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita,” ucap Tsaman, seraya membelai kepalaku lembut. “Kau pernah dengar gurindam itu, Nak? Itu adalah gurindam karya Raja Ali Haji Fasal 3. Kau tahu apa maksudnya?”
Aku menggeleng. Tsaman tersenyum lalu membelai rambutku.
“Jika kau menjaga apa yang kau lihat, maka kau tak akan banyak menyimpan keinginan dalam hatimu. Tapi, rupanya matamu telah menuntunmu untuk melihat apa yang kau inginkan. Nasi telah menjadi bubur. Lakukanlah apa yang menurutmu benar, Nak.”
Aku terkesiap. “Terima kasih, Tsaman. Terima kasih!” seruku bahagia.
“Tapi Anakku, aku hanya ingin berpesan padamu satu hal. Dengan bersekolah, kau kelak pasti akan membawa perubahan besar pada kehidupan suku laut. Tsaman harap perubahan itu datang untuk mengubah apa yang telah lebih dulu ada agar menjadi lebih baik. Bukan malah mengganti serta menghilangkannya.”
NAMAKU AZUREA. Anak suku laut pertama yang mampu memijakkan kakinya di lantai sekolah dasar. Gadis kecil dengan mimpi besar untuk dapat melihat dunia. Mencari warna terindah demi memperbaiki kehidupan suku laut tercinta. Suku yang telah melahirkan pelaut-pelaut andal perairan Riau. Suku tempat aku lahir dan belajar akan arti kehidupan.
Jika pagi buta anak-anak suku laut lain masih terlelap dalam bilik sampan mereka, aku tak pernah malas untuk bangun dan mendayung sampanku ke pesisir. Jika anak-anak lain dapat bermain di laut sepanjang hari, aku tak pernah mengeluh menghabiskan waktu belajar bersama teman-teman di sekolah.
Hari demi hari, bulan demi bulan. Tak terasa sudah 6 tahun aku bersekolah. Banyak ilmu yang aku dapat. Banyak teman yang aku kenal. Banyak hal baru yang aku tahu. Tapi, itu tak membuatku puas dan berhenti bersekolah.
Semenjak Tsaman memberikan izin aku untuk bersekolah, Ampu, Abah, dan Alun menjadi sangat mendukung niatku menuntut ilmu setinggi-tingginya. Abah bekerja keras agar dapat membiayai sekolahku. Ampu tak pernah bosan menyiapkan segala keperluan sekolahku. Dan Alun, dialah yang paling berjasa besar mengantarku sekolah tiap pagi ke pesisir. Alun juga yang menjemputku sepulang sekolah.
Akhirnya, aku melanjutkan ke sekolah menengah di kota. Karena jarak dari pesisir ke kota cukup jauh, Abah membelikanku sepeda dari hasil uang tabungan Ampu dan Alun. Memang hanya sebuah sepeda unta tua bekas yang dibeli di pasar, tapi sungguh aku merasa sangat senang. Aku merasa menjadi anak suku laut paling beruntung karena memiliki keluarga sebaik mereka.
Sampai pada ketika aku telah lulus sekolah menengah, aku tak sanggup berkata pada Abah, Ampu, dan Alun bahwa aku sangat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Aku tahu, pasti Abah tak punya biaya dan sangat berat bagiku untuk meninggalkan suku laut dan merantau ke Pekanbaru, Riau. Tempat Universitas Riau berada, satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau.
“Soleram, sol soleram, soleram anak yang manis, anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium, merahlah pipinya.”
MALAM INI, seperti malam itu. Saat Ampu menyanyikan dodoi untukku. Saat angin malam berembus kencang, saat bintang-bintang di langit bertaburan dan aku tak rela terlelap cepat serta meninggalkan keindahan malam yang selama ini selalu aku kagumi.
Aku menyandarkan kepalaku di atas paha Ampu. Mengenang masa-masa dulu seraya menikmati bintang-bintang di langit. Tak sengaja bola mataku menangkap sebuah bintang biru besar seperti beberapa tahun silam. Aku tersenyum padanya. “Ampu, lihat itu. Bintang itu masih di sana. Bintang biru besar yang sangat cantik,” ucapku lirih pada Ampu seraya menunjuk bintang itu.
Ampu mendongak. Sedetik kemudian mata Ampu berkaca, beliau menangis. Menciptakan dua aliran sungai kecil di pipi halusnya. Membuatku bangkit dari tidur dan duduk menghadap Ampu, mengelus pipinya sayang seraya meghapus air mata yang deras jatuh dari mata beliau.
“Ampu kenapa menangis? Adakah perbuatan Azurea yang melukai hati Ampu?” bisikku lirih. Hatiku perih melihat Ampu yang bahkan tak pernah bersedih menangis tersedu seperti itu.
Ampu mengusap air matanya. “Alun, tolong ambilkan surat yang kemarin Abah bawakan!” seru ampu pada Alun yang sedang rebah di dalam bilik sampan. Beberapa menit kemudian Alun datang, membawa sepucuk amplop besar dengan kop Universitas Riau di atasnya. Aku tercekat. Dengan tergesa aku membuka amplop itu.
Dengan surat ini, kami nyatakan bahwa pengajuan beasiswa penuh atas nama Azurea Balia Zasman, telah disetujui oleh pihak Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Indonesia.
Aku menangis. Aku haru dalam syukur nikmat yang Tuhan limpahkan padaku. Aku merasa seakan meraih bintang di langit. Aku bahagia. Ini semua seakan mimpi.
“Maaf, Ampu tak memberikan surat ini jauh-jauh hari padamu, Nak. Ampu tak kuasa jika kau harus pergi meninggalkan Ampu dan merantau ke Riau. Ampu tak ingin berpisah darimu!” ucap Ampu di sela isak tangisnya, lalu memelukku hangat.
Tubuhku bergetar hebat. Dunia seakan berputar di sekelilingku. Napasku terasa sesak, aku pun terisak dalam dekapan Ampu. Air mata mengalir deras dari mataku. Aku tak kuasa menahan kebahagiaanku dan meresapi duka bahagia yang Ampu rasakan.
Aku melepas pelukan Ampu. “Ampu, Alun, bagaimana bisa aku mendapatkan persetujuan beasiswa ini? Aku tak merasa pernah mengirimkan surat pengajuan!”
“Azurea sayang, kami mendengar apa yang kau pikirkan. Kami melihat apa yang kau rasakan. Kami tahu, apa keinginanmu,” ucap Alun. Aku tak tahu mimpi apa aku nanti malam, atau justru tak akan bisa tidur karena membayangkan menjadi mahasiswa Universitas Riau. Aku sungguh bersyukur menjadi Azurea. Gadis suku laut pertama yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Riau. Yang akan terus berjuang untuk mengejar mimpinya melihat dunia.
NAMAKU AZUREA. Suatu malam, Ampu pernah berpesan padaku untuk senantiasa menjaga laut yang sangat Abah cintai. Mungkin aku telah menentang resam suku laut, tapi aku tak pernah melupakan pesan Ampu untuk tetap menjaga suku laut seperti menjaga denyut nadiku.
Catatan:
Lanun = bajak laut
Dodoi= nyanyian sebelum tidur
Resam = adat
Pukau = sihir
Roman = raut
Tsaman = pemimpin, pemuka
Rud Yuneko Tunggadewi
Topic
#FiksiFemina